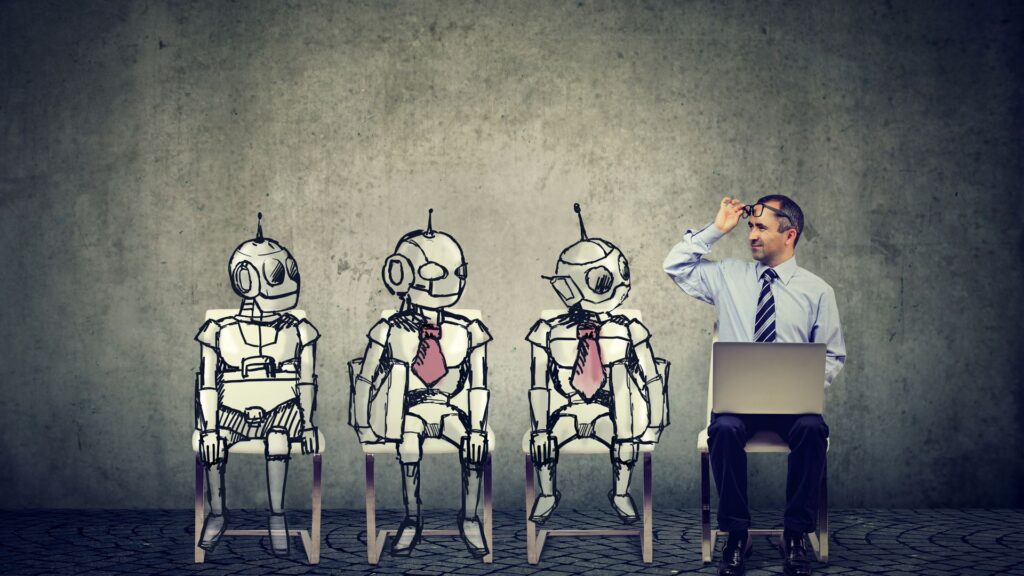Pernah suatu hari aku mengeluh kepada mentorku soal Turnitin. Waktu itu, kasusnya adalah bahwa masih terdapat beberapa persen kemiripan dalam tulisan hasil project kami. Padahal, aku pikir kemiripan antar kata adalah hal yang wajar, dan tidak seharusnya itu jadi masalah. Sampai sekarang, aku tidak paham bagaimana cara kerja Turnitin tersebut. Well, karena Turnitin “dianggap” objektif, jadi kita hanya bisa menyesuaikan.
Kemudian, muncullah ChatGPT. Personally, ChatGPT adalah aplikasi yang ajaib. Seperti kantong doraemon yang bisa melakukan banyak hal: menulis, memperbaiki tata letak kata, meninjau hasil tulisan, dan membuat konten. Bahkan, ada temanku yang ngobrol dengan ChatGPT soal nama yang keren untuk anaknya kelak. I mean, is there not a human to be discussed with?
Tidak hanya ChatGPT, aplikasi desain berbasis kecerdasan buatan (AI) juga sangat menarik. Orang yang tidak punya kemampuan desain pun bisa menghasilkan lukisan yang sangat indah. Ada kasus di mana dalam suatu lomba desain, seorang peserta memenangkan lomba dengan melukis menggunakan aplikasi AI.
Apa konteksnya aku bicara soal kasus-kasus AI di awal? Bagiku cukup tepat untuk mengatakan bahwa aplikasi AI membawa dampak yang signifikan – entah itu positif atau negatif. Beberapa orang menyebut AI mendemokratisasi media. Inti dari bahasa teknis itu adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan khusus bisa melakukan sesuatu. Namun, konsekuensi yang lebih besar dari adanya teknologi ini masih tidak diketahui.
AI dalam Dunia Bisnis: Hadiah dari Langit
Dunia usaha dan dunia industri mungkin sekarang mulai bergeser untuk lebih memberikan dampak sosial dan lingkungan. Tuntutan itu sudah mulai ada, terlebih menurut riset dari Cushman & Wakefield tahun 2024, 60% investor global mengatakan bahwa investasi di Environment, Social, and Governance (ESG) menghasilkan hasil kinerja yang lebih tinggi. Menurut studi dari KPMG tahun 2024, kecerdasan buatan dapat meningkatkan penerapan prinsip ESG. Makanya, investasi perusahaan terhadap AI akan terus meningkat. Survei dari Ernst & Young tahun 2024 pun menuturkan bahwa investasi di sektor AI membawa tiga manfaat: efisensi operasional (77%), produktivitas karyawan (74%), dan kepuasan pelanggan (72%).
Aku akan ambil dua cerita untuk lebih menggambarkan dampak AI di dunia bisnis. Pertama, aku akan cerita tentang Nike. Sebagai shoes brand ternama, sudah tidak diragukan lagi bagaimana pendekatan Nike terhadap inovasi. Adanya AI membuka banyak peluang dan kesempatan yang sebelumnya tidak ada. Dengan AI, Nike bisa meningkatkan pengalaman pelanggan dalam hal pengukuran sepatu yang sangat akurat, meningkatkan kecepatan, akurasi, dan keberlanjutan. Nike juga bekerja sama dengan perusahaan IT Cognizant untuk mengotomatisasi operasional Nike agar produktivitasnya meningkat dan menghemat biaya.
Cerita kedua datang dari salah satu perusahaan media terkenal, yaitu Axel Springer. Perusahaan ini memiliki perusahaan anak yang bernama Politico, salah satu media internasional paling berpengaruh di bidang politik. Axel Springer menjalin kerja sama dengan OpenAI untuk mengintegrasikan AI di jurnalisme. Inisiatif ini memungkinkan pengiriman konten yang disesuaikan secara real-time ke ChatGPT, termasuk ringkasan artikel berbayar. Tidak hanya itu, kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan traffic dan pendapatan dari subscription.
Dua cerita di atas menunjukkan bahwa AI mungkin adalah jawaban yang diberikan langit terhadap upaya perusahaan untuk memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi. Memang butuh penyesuaian di sana-sini, tapi melihat tren saat ini, penggunaan AI akan semakin mendominasi di dunia usaha dan dunia industri. Jika aku adalah pemimpin atau CEO dari dua perusahaan tersebut, tentu aku akan memanfaatkan AI secara optimal supaya performa perusahaan meningkat.
Mengikis Otonomi Manusia
Namun, aku tidak hanya melihat dampak AI dari satu sudut pandang semata. Bagaimana dengan habit, kemampuan, dan proses kita dalam melakukan sesuatu? Itu benar kalau AI memudahkan kita, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bingung dalam memilih sesuatu, kita hanya tinggal bertanya pada ChatGPT. Atau kita ingin membuat suatu gambar, kita bisa ke Dall-E dan mengetikkan prompt yang kita bayangkan. Voila! Gambar pun diciptakan hanya dalam hitungan menit.
Bagaimanapun, ada satu perspektif yang memicuku memikirkan ulang bagaimana relasi kita dengan teknologi, dengan AI. Ethan Mollick, profesor dari the Wharton School Universitas Pennsylvania, menggambarkan ini dengan sangat tepat dalam bukunya yang berjudul “Co-Intelligence: Living and Working with AI”. Merangkum dari Fortune, Mollick melukiskan bahwa ketika dihadapkan oleh tirani lembar kosong, orang akan menekan tombol The Button. Memang lebih mudah untuk memulai dengan sesuatu dibandingkan tanpa sesuatu.
Namun, ada dua konsekuensi dari kita melakukan itu. Konsekuensi pertama adalah kita jadi kehilangan kreativitas dan originalitas. Dalam konteks apapun, karya kita jadi dipengaruhi oleh AI, meskipun kita melakukan editing sendiri. Konsekuensi kedua adalah kita mengurangi kemampuan dalam depth thinking. Kita jadi tergantung oleh mesin dalam untuk menganalisis dan mensintesis. Alhasil, kita jadi tidak terlibat dalam berpikir reflektif dan kritis.
I won’t say that using AI is a bad thing. Tetapi, seperti pepatah pernah katakan bahwa too much is not serves you any good. Kata kuncinya adalah terlalu berlebihan. Riset dari MIT pada tahun 2023 menemukan, ternyata ChatGPT menjadi pengganti dari usaha manusia, bukan sebagai pelengkap dari kemampuan kita.
Ini yang menurutku menjadi bahaya. Setiap teknologi ada sebagai pelengkap dan pembantu, bukan sebagai pengganti. Dan nyatanya, kita sendiri yang justru menyerahkan otonomi kita dalam berpikir reflektif, kritis, dan analitis kepada AI. Kalau kita melakukan itu secara terus menerus, berpikir analitis dan kritis bukan lagi ciri khas manusia apabila fungsi itu kita serahkan kepada teknologi.Aku kemudian berpikir bagaimana respon Leonardo da Vinci jika dia hidup di masa ini. Mungkin dia awalnya akan takjub melihat kemampuan AI yang luar biasa, bahkan bisa meniru lukisannya yang proses penciptaannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, bisa jadi, dia akan kembali pada proses berpikir yang old school, yaitu melalui observasi, dialog, dan refleksi.
Apakah Perlu Garis Batas?
Di tengah gempuran berbagai aplikasi AI, tumpukan pekerjaan, dan terbatasnya waktu dan energi kita, adanya AI sangat membantu. Akan tetapi, kita perlu memberi batasan sejauh mana kita menggunakan teknologi, supaya posisi mereka hanya sebagai pelengkap, bukan pengganti.
Kita saat ini sedang mengalami progress AI yang signifikan. Akan muncul aplikasi-aplikasi baru – atau update dari aplikasi sebelumnya – yang semakin memperbanyak pilihan kita. Kita mungkin akan menyerahkan sepenuhnya pada AI jika kita terlalu lelah. Tapi, di sisi lain, kita jadi lebih pandai menulis prompt yang detail dan akurat. Itu satu kemampuan yang sangat berharga di era sekarang, namun kurang berharga apabila kita harus kehilangan otonomi dalam berpikir kritis, analitis, dan reflektif.
Menurutku, kita perlu garis batas dalam memanfaatkan kecerdasan buatan. Caranya adalah dengan mendefinisikan cara hidup dan norma hidup dengan mempertimbangkan keberadaan AI. Kita butuh semacam guidances baru yang membuat kita bisa menavigasikan bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, tanpa menyerahkan sisi yang otentik dalam diri kita. Karena perkembangannya sangat cepat, kita belum sempat berhenti sejenak dan memikirkan jawaban dari pertanyaan, “Bagaimana dampak keseluruhan AI pada kehidupan kita?”
Apalagi, di kehidupan sekarang, cara hidup kita semakin absurd karena AI. Harusnya kita perlu lebih banyak berhenti untuk mempertanyakan dampak ciptaan kita.